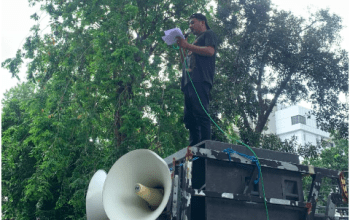Nusatoday.id – Dalam politik, loyalitas adalah mata uang yang mahal. Namun di tangan seorang politisi seperti Sufmi Dasco Ahmad, loyalitas bukan sekadar kesetiaan, melainkan ujian keseimbangan antara prinsip dan pragmatisme. Ia berdiri di persimpangan yang rumit: di satu sisi, sebagai kader Gerindra yang wajib menjaga soliditas partai; di sisi lain, sebagai pimpinan DPR yang dituntut menegakkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah yang juga didukung partainya.
Di sinilah loyalitas berpotensi menjelma jebakan. Ketika garis kebijakan partai terlalu mesra dengan agenda eksekutif, fungsi parlemen rawan berubah menjadi stempel formalitas. Publik pun berhak bertanya: apakah DPR di bawah kendali figur seperti Dasco benar-benar mampu menjaga jarak kritis terhadap pemerintah? Ataukah independensi legislatif kian larut dalam euforia koalisi?
Pertanyaan itu tak lahir dari prasangka kosong. Sejumlah pengamat menilai, posisi strategis Dasco di DPR bisa menumpulkan daya gigit lembaga yang semestinya menjadi penyeimbang kekuasaan. Tapi, di sisi lain, tak sedikit yang mengakui peran stabilisnya. Dalam lanskap politik yang penuh riak dan ego sektoral, keberadaan Dasco disebut turut menjaga suhu politik tetap moderat setidaknya di permukaan.
Namun stabilitas tanpa daya kritik hanyalah ketenangan semu. Parlemen yang jinak mungkin membuat pemerintah nyaman, tapi sekaligus menjauhkan rakyat dari suara pengawasan yang sejati. Di titik inilah Dasco menghadapi paradoks kepemimpinan: bagaimana menegakkan loyalitas tanpa menanggalkan independensi, bagaimana menjadi bagian dari kekuasaan tanpa kehilangan jarak dari kuasa itu sendiri.
Pada akhirnya, sejarah politik tidak diingat dari siapa yang paling setia, melainkan siapa yang berani menjaga akal sehat di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Dalam dunia politik yang kian kabur batasnya antara dukungan dan pembenaran, mungkin itulah loyalitas yang sesungguhnya: bukan kepada partai, bukan kepada pemerintah, melainkan kepada kepentingan rakyat.